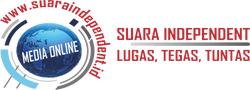Wali Kota Gunungsitoli Dan Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli Tandatangani Nota Kesepakatan
 GUNUNGSITOLI, SUARA INDEPENDENTNEWS.ID
GUNUNGSITOLI, SUARA INDEPENDENTNEWS.ID
Wali Kota Gunungsitoli dan Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli tandatangani Nota Kesepakatan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022. Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Gunungsitoli, Jumat (28/07/2023).
Sebelum penandatanganan Nota Kesepakatan, agenda rapat diawali dengan laporan Badan Anggaran dan penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Kota Gunungsitoli terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 yang secara keseluruhan dapat memahami dan menerima Ranperda dimaksud untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Wali Kota Gunungsitoli Ir. Lakhomizaro Zebua dalam pendapat akhir, mengapresiasi dukungan dan saran konstruktif yang diberikan oleh segenap Anggota Dewan selama proses pembahasan Ranperda ini berlangsung, sehingga Ranperda dimaksud dapat ditetapkan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.
“Mencermati pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli TA. 2022 secara umum dapat kami pahami, demikian juga halnya beberapa saran rekomendasi peningkatan dan optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan akan menjadi perhatian pemerintah daerah dengan tetap mengharapkan dukungan sinergitas dan kolaborasi dari Lembaga DPRD serta pemangku kepentingan lainnya,” ujar Wali Kota.
“Mengakhiri pendapat akhir ini, kami nyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 sepakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tutup Wali Kota.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli, Sekretaris DPRD Kota Gunungsitoli, dan hadirin lainnya. (Aa Wahyu)